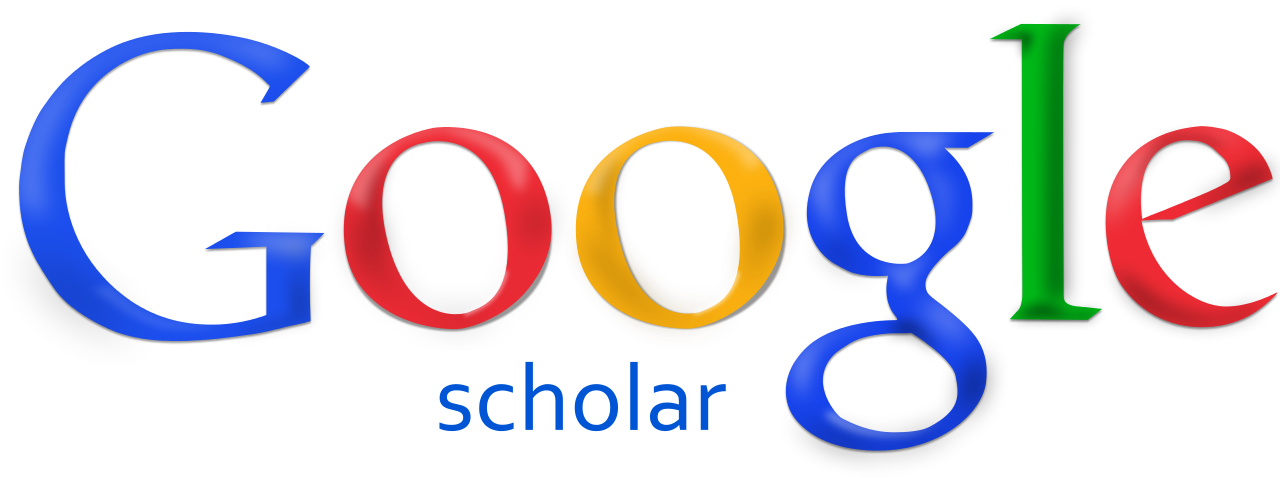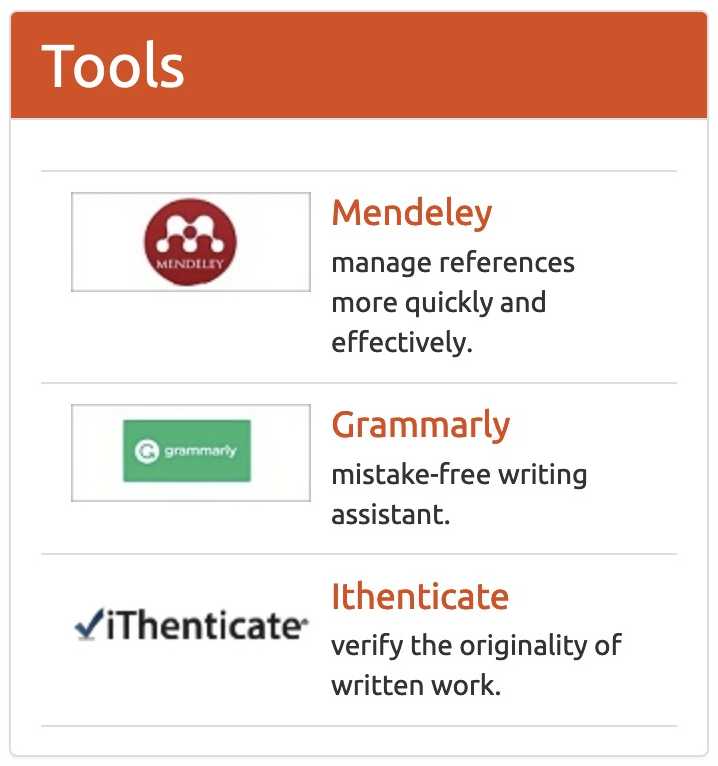Faktor - Faktor Prediktor Kegagalan Terapi High Flow Nasal Cannula pada Pasien Sakit Kritis dengan Covid-19 di Unit Perawatan Intensif
Abstract
Latar Belakang: Sistem penilaian yang dipakai dan lazim digunakan di Intensive Care Unit (ICU) untuk memprediksi outcome terapi High Flow Nasal Cannula (HFNC) adalah melalui ROX Index. ROX index adalah skor yang telah tervalidasi berdasarkan terapi yang diberikan pada pasien Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) dan pneumonia. Kehandalan ROX Index dalam memprediksi kegagalan terapi HFNC sudah diakui secara luas, namun masih diperlukan prediktor lain yang lebih akurat dan cepat.
Tujuan: Mengetahui skor Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), kadar ferritin, Rasio Neutrofil Limfosit (RNL), kadar D-Dimer serta C-Reactive Protein (CRP) sebagai prediktor kegagalan terapi HFNC pasien sakit kritis dengan COVID-19 di ICU.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif case control dengan mengambil data rekam medis pasien sakit kritis dengan COVID-19 yang menggunakan terapi HFNC di ICU Infection Center RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sampel adalah seluruh populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi. Data yang memenihi kriteria ditabulasi menggunakan Microsoft Excel, analisis menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows 25.0. Analisis dilakukan secara bertahap, meliputi analisis deskriptif, analisis bivariat (data diolah menggunakan T Test atau Mann Whitney U Test). Dilakukan juga analisis regresi logistik untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel sebagai suatu prediktor
Hasil: Terdapat perbedaan yang bermakna skor SOFA (p value = 0.027), parameter Ratio Neutrofil Limfosit (p value = 0.014), dan kadar C-Reactive Protein (p value =0.046) terhadap kelompok Sukses Terapi HFNC dan Gagal Terapi HFNC (p=0.027). Tidak terdapat perbedaan yang bermakna kadar feritin (p value = 0.747) dan kadar D-Dimer (p value = 0.251) terhadap kedua kelompok. Uji regresi logistik menunjukkan bahwa yang dapat digunakan sebagai prediktor adalah nilai Skor SOFA (p=0.017) dan RNL (p= 0.046), sedangkan variabel lain memiliki nilai p > 0.05
Simpulan: Skor SOFA dan Rasio Neutrofil Limfosit (RNL) dapat digunakan sebagai prediktor kegagalan terapi HFNC pada pasien sakit kritis dengan COVID-19 di ICU.
Copyright (c) 2022 Ridwan, Syamsul Hilal Salam, Haizah Nurdin, Andi Husni Tanra, Faisal Muchtar, Ari Santri Palinrungi, Andi Alfian Zainuddin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.